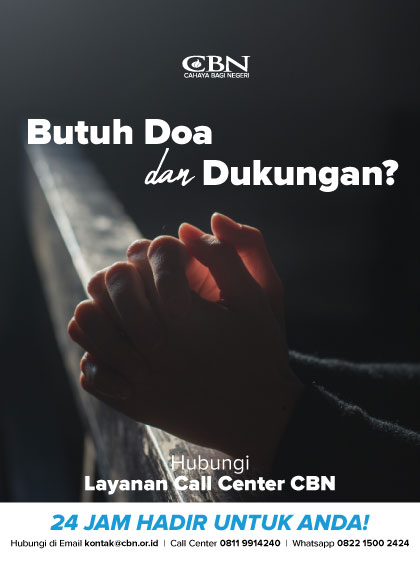Nasional / 2 June 2007
Sekolah Tak Lagi Menyenangkan

Puji Astuti Official Writer
JAWABAN.com - Kasihan anak sekolah sekarang, terutama bagi yang duduk di kelas "akhir" dan harus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sekolah, les, belajar, ujian, itu bulak-balik. Anak yang duduk di kelas 6 SD, kelas 9 (SMP kelas 3), kelas 12 (SMA kelas 3), benar-benar "diperas" oleh situasi dan keadaan. Tak ada lagi waktu bersantai, kalau pun ikut rekreasi bersama keluarga, terpaksa harus membawa buku, dan mencari-cari waktu untuk belajar. Tak saja dirasakan pelajar di Ibu kota tapi juga di kota-kota besar lainnya. Para orang tua bingung, anak yang satu minta liburan, anak yang lain menghadapi ujian. Orang tua yang memiliki anak-anak di usia tersebut tak lagi bisa berlibur panjang, santai dan berekreasi bersama-sama anak-anaknya itu, malah sebaliknya, tampak stres dan lelah. Belum lagi bicara masalah biaya.
Aline dan Ike, siswi kelas 12 SMU Kolese Gonzaga, yang biasanya di hari Minggu aktif di Komisi Remaja, sejak lama mengatakan, "tidak banyak waktu luang lagi sejak duduk di kelas 3. Jadwal belajar dan bimbel (bimbingan belajar, Red) padat, selain ujian nasional (UN), ujian sekolah, juga mikirin tes perguruan tinggi. Stres rasanya", kata mereka serempak. Aline bercerita, sejak semester satu, ikut bimbel. Ike malah sejak kelas satu karena jurusan IPA. Bulan Desember lalu Universitas Atmajaya sudah buka gelombang satu penerimaan mahasiswa baru. Aline ikut pada gelombang dua, Januari lalu, dan sudah diterima. Ike mencoba jalur mandiri dan SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru). "Bayangkan, dari Januari sudah tes perguruan tinggi, lalu ada pra-UN, UN, ujian praktek, ujian sekolah. Yang ikut jalur mandiri tes duluan, baru SPMB. Hidup kita dipenuhi ujian. Bagi kami yang paling menakutkan itu ya UN karena kalau nilainya di bawah standar bisa tidak lulus", kata Aline.
Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Dr Daniel M Rosyid, yang dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya kepada SP mengatakan, setiap siswa memiliki tingkat adaptasi yang berbeda menghadapi stres menjelang pelaksanaan Ujian Nasional. ''Bagi siswa yang memili kecerdasan emosional yang baik, tentu bisa memperkecil tingkat stressor. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, anak-anak kita yang memiliki kecerdasan emosional. Nah celakanya, sistem pendidikan nasional kita tidak memberikan pendidikan yang bisa meningkatkan kecerdasan emosional, karena hanya menitikberatkan kecerdasan intelektual,''katanya. Dia tetap berprinsip UN hendaknya hanya untuk memetakan kualitas dan kuantitas pendidikan nasional yang dilakukan secara sampling, sehingga tidak harus menentukan kelulusan siswa. "Dari hasil pemetaan kualitas dan kuantitas pendidikan itulah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan perbaikan tetapi sekarang ini perbaikan tidak pernah dilakukan tetapi UN tetap berjalan terus'', katanya. Menjelang UN, siswa kelas 3 SMP dan SMA di berbagai kota ada yang melakukan istighotsah atau doa bersama pada pagi. Bahkan ada yang sembahyang lewat tengah malam atau sholat tahajut. ''Ini merupakan pendekatan agamis untuk menekan stress , tekanan psikologis yang sangat berat karena kelulusan siswa hanya ditentukan melalui ujian selama tiga hari saja, padahal proses pendidikan berlangsung selama tiga tahun, di mana para guru terlibat langsung,''katanya.
Daniel yang anaknya juga mengikuti UN SMA mengaku, harus mengeluarkan biaya lebih banyak. Anaknya harus membayar les sebesar Rp 100.000/bulan atau lebih mahal dibandingkan biaya SPP sebesar Rp 75.000/bulan. Belum lagi ongkos menuju ke tempat les, mulai sekolah sampai tempat-tempat bimbel. Diakui, selama enam bulan menjelang UN, atau bisa saja sejak siswa mengawali pelajaran di kelas tiga, siswa dan guru tidak bisa menjalani proses pendidikan dengan ''enjoy'', karena sekolah mendapatkan target jumlah kelulusan siswa di tengah-tengah kenaikan nilai kelulusan. Ribuan siswa jadi "korban'' ketidaklulusan UN di Jawa Timur. Siswa SMA yang tidak lulus sekolah di Jatim pada UN tahun 2006 lalu tercatat sebanyak, 9.948 siswa SMA/MA. Program Studi IPA yang tidak lulus sebanyak 4.518 siswa atau sekitar 8,08 persen dari 55.918 peserta UN. Sementara program IPS yang tidak lulus 5211 siswa atau sekitar 14 persen dari 37.228 peserta UN. Siswa SMK yang tidak lulus sekitar 21.223 siswa atau sekitar 19 persen dari 111.700 siswa . Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP yang tidak lulus sebanyak 24.347 siswa atau sekitar 9,998 persen dari 243.960 siswa peserta UN.
Menurut Prof Dr Amin Rasyid, Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dulunya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), pemberian pelajaran tambahan melalui les atau kursus-kursus kepada siswa di luar jam sekolah, baik di jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas, menunjukkan adanya indikasi bahwa sekolah belum mampu memenuhi penerapan pelajaran dalam sesi-sesi pertemuan di setiap kelas per jam. Salah satu alasannya, kemungkinan karena terlalu banyak jenis mata pelajaran yang diajarkan di setiap jenjang. Sehingga, jam pertemuan siswa dan guru pengajar yang hanya 45 menit dan dihitung menjadi satu jam pertemuan, itu dirasakan belum cukup, apalagi jika mata pelajaran itu sendiri memerlukan latihan.
"Kondisi itulah menyebabkan siswa memilih belajar ekstra di luar jam sekolah sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan di sekolah," katanya kepada SP. Amin yang juga salah seorang Ketua tim Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Kependidikan Bidang Perpustakaan Depdiknas, lebih jauh menambahkan, belajar ekstra di luar sekolah juga dilakukan karena tujuan yang akan dicapai tidak selaju proses yang dapat dilaksanakan di kelas. Maka, salah satu kompensasinya, anak yang merasa tidak puas itu mengambil kursus-kursus di luar yang sebenarnya tidak perlu terjadi hal seperti itu kalau saja semua yang dibutuhkan dapat terpenuhi di sekolah. "Lebih tidak beres lagi kalau yang mengajar dalam proses pelajaran ekstra itu adalah gurunya sendiri," tandasnya.  Sekolah seharusnya terfasilitasi dengan baik, bukan hanya dengan jam tatap muka disekolah, tetapi harus disediakan laboratorium di mana anak itu bisa mengakses informasi tanpa guru, apalagi kalau ada perpustakaan yang lengkap, ada internetnya. "Jadi, kalau terfasilitiasi dengan baik, anak-anak bisa menambah pengetahuannya sendiri tanpa harus mengikuti penambahan pendidikan ekstra. Tentu saja untuk mengadakan fasilitas pendidikan seperti itu memerlukan biaya yang cukup besar," kata Amin. Menjawab pertanyaan tentang efek pemberian beban tambahan bagi siswa di luar jam sekolah, pakar pendidikan kelahiran Gillireng, Kabupaten Wajo itu mengatakan, dari segi teori belajar, semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar maka semakin banyak yang diketahui. Namun, tentu saja ada efek pengiringnya dan yang paling nampak adalah pengorbanan waktu, energi maupun finansial. Sebenarnya, kata Amin, sangat diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengatasi kelemahan siswa di sekolah. Namun, saya melihat ada upaya orang tua siswa mau memperingan bebannya dengan pendidikan anaknya. Pola pikir seperti itulah yang harus diubah, sebab anak merupakan investasi dan untuk menjadikan dia sebagai investasi yang bermanfaat, orang tua harus berani berkorban untuk itu. Menurutnya, kesadaran orang tua siswa untuk memberikan kesempatan anaknya mengikuti pelajar ekstra di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan, adalah pola pikir yang harus ditiru. Di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri yang dikenal sebagai daerah lumbung pangan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum menganggap bahwa pendidikan itu sebagai investasi jangka panjang.
Sekolah seharusnya terfasilitasi dengan baik, bukan hanya dengan jam tatap muka disekolah, tetapi harus disediakan laboratorium di mana anak itu bisa mengakses informasi tanpa guru, apalagi kalau ada perpustakaan yang lengkap, ada internetnya. "Jadi, kalau terfasilitiasi dengan baik, anak-anak bisa menambah pengetahuannya sendiri tanpa harus mengikuti penambahan pendidikan ekstra. Tentu saja untuk mengadakan fasilitas pendidikan seperti itu memerlukan biaya yang cukup besar," kata Amin. Menjawab pertanyaan tentang efek pemberian beban tambahan bagi siswa di luar jam sekolah, pakar pendidikan kelahiran Gillireng, Kabupaten Wajo itu mengatakan, dari segi teori belajar, semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar maka semakin banyak yang diketahui. Namun, tentu saja ada efek pengiringnya dan yang paling nampak adalah pengorbanan waktu, energi maupun finansial. Sebenarnya, kata Amin, sangat diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengatasi kelemahan siswa di sekolah. Namun, saya melihat ada upaya orang tua siswa mau memperingan bebannya dengan pendidikan anaknya. Pola pikir seperti itulah yang harus diubah, sebab anak merupakan investasi dan untuk menjadikan dia sebagai investasi yang bermanfaat, orang tua harus berani berkorban untuk itu. Menurutnya, kesadaran orang tua siswa untuk memberikan kesempatan anaknya mengikuti pelajar ekstra di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan, adalah pola pikir yang harus ditiru. Di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sendiri yang dikenal sebagai daerah lumbung pangan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum menganggap bahwa pendidikan itu sebagai investasi jangka panjang.
Sementara itu, menurut psikolog Seto Mulyadi, arah pendidikan saat ini, sebagian besarnya menjerumuskan beragam sumberdaya manusia negeri ini ke arah penyeragaman dan menjadikan robot. Lingkar-lingkar kreativitas dan daya pikir kritis telah dimatikan secara struktural. "Kita bisa lihat penyeragaman itu. Mulai dari pakaian, hingga buku-buku pelajaran. Padahal, setiap siswa adalah berbeda. Ada yang cerdas di bidang matematika, ada yang menyukai seni. Biarlah mereka tumbuh bagaikan bunga yang beragam indahnya. Pendidikan kita telah telanjur seragam," katanya. Seto mengemukakan, pendidikan adalah hak penuh anak bukan kewajiban pemerintah. Karena itu, anak memiliki hak di mana dia ingin belajar. "Sekarang banyak sekolah-sekolah yang menyebut seolah unggulan atau sekolah favorit. Padahal, banyak siswa yang belajar di sekolah itu mengalami depresi. Bahkan, bulan lalu ada salah satu siswa di sekolah unggulan yang hendak bunuh diri karena tidak kuat menahan beban pelajaran. Ini berarti belum tentu sekolah unggulan itu sesuai dengan kemauan anak," terangnya. Dikatakan, sudah saatnya orang tua sadar bahwa belajar adalah hak anak. Sehingga, kemauan untuk memilih sekolah mana yang hendak dituju bukanlah kemauan orangtua melainkan kemauan anak. "Jangan sampai memaksakan kehendak kepada anak untuk sekolah yang dianggap unggulan," katanya.
Bahkan, kata Seto, berdasarkan penelitian di Amerika, sekolah-sekolah yang dianggap 'tidak unggulan' justru menjadi berkualitas karena anak-anak yang belajar di sekolah itu merasa tidak tertekan. "Belajar harus menyenangkan," katanya. Dikatakan, ketika pendidikan masuk dalam bingkai kewajiban maka itu merupakan awal kehancuran. Seto menerangkan, penggiringan pendidikan anak negeri ke jurang kehancuran bermula pada meletakkan pendidikan sebagai sebuah kewajiban, sehingga tertancapkanlah pemikiran di seluruh keluarga di negeri ini bahwa pendidikan itu wajib. "Dengan semakin banyaknya pihak yang berkewajiban menjalani proses pendidikan formal, maka ini menjadikan pendidikan sebagai sebuah arena bisnis," katanya. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menegaskan bahwa dunia pendidikan masih diskriminatif. Padahal, ada kewajiban negara untuk memberikan pendidikan murah dan bermutu. "Ini kan sudah sesuai dengan Piagam Dakar. Yakni, piagam yang menyatakan pendidikan untuk semua dan itu bagian dari Millenium Development Goal's (MDG'S). Kalau ini saja diabaikan negara berarti negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hal pendidikan," katanya.(joe)